Akibat Salah Asuh sejak Lama
By Redaksi Pustakatani
Pertarungan batin dialami Suyoto (54), seorang petani dan petugas penyuluh lapangan di Kabupaten Sukoharjo. Ia tahu betul bahwa pertanian kimia tidak hanya merusak alam, tetapi juga berpengaruh buruk bagi kesehatan manusia.
Ia pun paham bahwa metode pertanian organik seharusnya bisa membuat petani lebih sejahtera karena biaya yang dikeluarkan bisa terus ditekan, sedangkan hasil yang diperoleh selalu meningkat.
Akan tetapi, embel-embel sebagai pegawai negeri yang harus tunduk pada peraturan pemerintah membuat Suyoto tidak bisa bebas menyuarakan pertanian organik. Apalagi konsep pertanian organik pemerintah adalah pertanian organik yang mendua, masih memakai campuran produk kimia. Kampanye organik masih diikuti dengan penjualan urea.
Sebaliknya, pendampingan bagi petani agar beralih ke pertanian organik juga belum dilakukan secara intensif. "Paling-paling hanya satu musim. Setelah itu, proyek pendampingan petani berhenti," katanya. Pendekatan yang sama juga dilakukan sejumlah LSM.
Jika prosesnya seperti itu, Suyoto sangsi bisa membantu petani kembali ke pertanian organik. Apalagi pengalihan pertanian konvensional (yang terlanjur non-organik dan jenuh pestisida) ke pertanian organik tak sebatas alih metode pertanian, tetapi juga peralihan ideologi kemandirian yang lepas bebas dari ketergantungan pada pihak lain.
Ketergantungan sarana produksi pertanian konvensional terlihat jelas pada kebutuhan petani akan bibit, pupuk, hingga pestisida. Harga sarana produksi itu ditentukan oleh pabrik dan pemerintah. Begitu pula dengan kontrol pemerintah atas harga beras sehingga petani tidak punya posisi tawar untuk menaikkan kesejahteraan mereka.
Sebagai petani, Suyoto pun belum maksimal menerapkan teknik pertanian organik. Karena doktrin pertanian konvensional yang berlangsung puluhan tahun, Suyoto masih malu dengan petani di kanan-kirinya untuk mengganti pupuk urea dengan pupuk kompos.
Apalagi percobaan penanaman padi dengan metode organik total hanya menghasilkan gabah tidak lebih dari 50 persen dibandingkan hasil dari pertanian hijau. Akhirnya, ia hanya memilih untuk tidak memakai pestisida sama sekali, tetapi masih mengandalkan pupuk urea. "Inilah akibat dari salah asuh yang sudah terlalu lama," kata Suyoto sambil tertawa.
TO Suprapto, Koordinator Nasional IPPHTI, juga mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menetapkan tahun 2010 sebagai tahun pertanian organik. Bila tahun 2010 disasar sebagai tahun pertanian organik, seluruh komponen yang mendukung pertanian organik perlu disiapkan.
Salah satu contoh kecil adalah minimnya data tentang pertanian organik di hampir semua institusi dinas pertanian di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Gerakan pertanian organik masih berupa aksi-aksi kecil di tingkat individu, dusun atau desa yang—biasanya—merupakan daerah dampingan suatu kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat.
"Karena itu, saya mengusulkan kampanye hasil pertanian organik sebagai produk sehat. Selain itu, pertanian organik harus meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi tidak memberatkan konsumen karena akan percuma saja bila produksi meningkat, namun daya beli masyarakat rendah," kata Suprapto.
Dalam perhitungan matematis produksi pertanian konvensional, petani bisa jadi hanya menjadi buruh sukarela untuk menanam dan merawat tanaman. Tenaga mereka sering kali tidak dimasukkan dalam komponen biaya produksi. Apalagi harga produk pertanian—terutama beras—bukanlah harga yang ditentukan petani sebagai produsen, melainkan harga yang sudah ditetapkan secara baku oleh pihak yang berkuasa (baca: pedagang dan pemerintah), melalui mekanisme pasar dengan berbagai dalih, seperti pengamanan stok pangan nasional.
Katamso, Ketua Kelompok Tani Organik Gemari di Dusun Jomboran, Desa Sendangagung, Minggir, Sleman, pernah menghitung besarnya pengeluaran untuk satu kali masa tanam. Harga satu kilogram bibit setara dengan sekilo beras, yakni antara Rp 3.500 hingga Rp 5.000 per kilogram. Untuk 1.000 meter persegi tanah dibutuhkan 5 kilogram bibit.
Sedangkan kebutuhan pupuk urea untuk tanah seluas 1.200 meter persegi mencapai 50 kilogram. Bila beruntung, petani bisa mendapatkan pupuk urea bersubsidi seharga Rp 52.500 untuk 50 kilogram. Selain urea, masih berjenis pupuk kimia lain yang harus dikonsumsi padi hibrid itu.
Pengeluaran petani masih ditambah dengan sejumlah komponen jasa, seperti ongkos traktor, membayar tenaga buruh tanam, dan biaya jasa lain. Belum lagi biaya untuk sewa tanah atau penyusutan lahan.
Untuk biaya produksi, petani harus merogoh hingga Rp 400.000. Hasil yang diperoleh sekitar 2,75 kuintal beras, untuk jenis panenan tergolong baik. Bila petani mengolah sendiri pascaproduksi seluruh, beras ini setara dengan Rp 962.500.
Namun, sejumlah pengeluaran pascapanen, seperti penjemuran serta penggilingan dari gabah menjadi beras, juga harus dilakukan sendiri. Belum lagi bila padi dikonsumsi sendiri, sekitar empat bulan masa tanam. "Mengerikan sekali kalau harus menghitung hasil pertanian kimia. Sepertinya, usaha petani tidak ada harganya," tutur Katamso.
Karena perhitungan yang begitu mencekik petani, Katamso memilih untuk menerima pelajaran bertani organik. Di bawah bimbingan petani dari Dusun Kleben, Godean, Sleman, Katamso dan belasan petani Jomboran belajar membuat pupuk kompos.
Keberpihakan
Di tengah mulai berakarnya pertanian organik yang telah dirintis selama 6 tahun, Suratman, petani di Dusun Temon, Desa Banyuaeng, Karangnongko, Klaten, justru memilih untuk meninggalkan metode pertanian organik dan kembali ke pertanian hijau.
Alasannya sederhana: rantai pemasaran yang selama ini dijalankan kelompok pertanian Sari Pratiwi mandek sejak tahun 2004. Akibatnya, ia lebih senang bertani secara praktis dengan memanfaatkan sarana produksi kimia.
"Hasil yang didapat dari pertanian organik juga tidak sebanyak pertanian dengan kimia. Karena itu, saya memilih memakai pupuk kimia dan pestisida saja."
Beras dari "pertanian hijau" (memakai urea) telah memberinya hasil lebih banyak. Sedangkan teknologi organik hingga kini belum bisa memberi hasil maksimal yang meyakinkan bahwa pertanian organik meningkatkan kesejahteraan.
Suratman dan petani lain banyak yang mengeluhkan problem pemasaran. Problem ini disebut-sebut juga oleh Direktur Komunitas Bunderan (UGM Yogyakarta) Gutomo Priyatmono sebagai salah satu masalah yang perlu dipecahkan untuk mendongkrak popularitas pertanian organik.
"Fokus kami pada perluasan pasar. Ketika pasar tidak ada, pertanian organik akan mati. Bila kita ingin menghargai produk pertanian organik, maka harga beli gabah petani tinggi. Akhirnya berujung pada mahalnya produk pertanian," ucap Gutomo.
Harga gabah organik yang tinggi memicu harga beras organik juga mahal. Buntutnya konsumen yang bisa membeli produk pertanian organik akan terbatas sehingga daya serap produk organik ini tidak bisa sebesar beras konvensional yang murah, apalagi beras raskin. Terpautnya harga setidaknya Rp 2.000 per kilogram.
Peneliti Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan (PSKP) UGM Mochammad Maksum menambahkan, akademisi di kampus merupakan pihak yang ikut melanggengkan pertanian kimia karena dari situ para akademisi memperoleh proyek.
"Coba Anda masuk perguruan tinggi. Faktanya, berjubel akademis nge-gong-i pendekatan kimiawi dan teramat langka yang melirik organik. Mengapa? Karena akademisi lebih suka proyek," ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Antonius Budisusila, mengatakan, trauma petani atas peristiwa tahun 1950-1960-an merupakan bagian dari politik ingatan yang membuat petani malas kembali memakai pertanian organik. Petani dihadapkan pada fakta orang antre bahan pangan dan penghapusan paksa memori bertani organik. Petani yang menolak sistem pertanian modern dengan bahan-bahan kimia akan dicap sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dari sisi struktural, petani menghadapi sejumlah masalah yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Petani penggarap tentu akan enggan beralih jadi petani organik.
Apalagi sewa tanah tidak dilakukan secara bagi hasil, melainkan dibayar tunai. Akibatnya, petani enggan mencoba metode pertanian yang dianggap "baru", seperti pertanian organik.
Di samping itu, petani menghadapi tawaran tiada henti untuk memperbesar keran konsumsi mereka dengan kemudahan mendapatkan kredit atau pinjaman (termasuk dari pemerintah).
Karena itu, sejumlah agenda reformasi agraria mendesak untuk segera dilaksanakan. Misalnya, membuka kesempatan petani mengakses tanah kas desa. Namun, kepentingan ini masih harus berhadapan dengan tuntutan meningkatkan pemasukan desa yang berbuntut pada keberpihakan desa kepada pemodal.
Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan. Apalagi dengan disertasi tentang masyarakat desa yang telah dilakukan pimpinan bangsa ini diharapkan kebijakan negara untuk ketahanan pangan bisa semakin dekat dengan petani sebagai produsen pangan (Agnes Rita Sulistyawaty)
Ia pun paham bahwa metode pertanian organik seharusnya bisa membuat petani lebih sejahtera karena biaya yang dikeluarkan bisa terus ditekan, sedangkan hasil yang diperoleh selalu meningkat.
Akan tetapi, embel-embel sebagai pegawai negeri yang harus tunduk pada peraturan pemerintah membuat Suyoto tidak bisa bebas menyuarakan pertanian organik. Apalagi konsep pertanian organik pemerintah adalah pertanian organik yang mendua, masih memakai campuran produk kimia. Kampanye organik masih diikuti dengan penjualan urea.
Sebaliknya, pendampingan bagi petani agar beralih ke pertanian organik juga belum dilakukan secara intensif. "Paling-paling hanya satu musim. Setelah itu, proyek pendampingan petani berhenti," katanya. Pendekatan yang sama juga dilakukan sejumlah LSM.
Jika prosesnya seperti itu, Suyoto sangsi bisa membantu petani kembali ke pertanian organik. Apalagi pengalihan pertanian konvensional (yang terlanjur non-organik dan jenuh pestisida) ke pertanian organik tak sebatas alih metode pertanian, tetapi juga peralihan ideologi kemandirian yang lepas bebas dari ketergantungan pada pihak lain.
Ketergantungan sarana produksi pertanian konvensional terlihat jelas pada kebutuhan petani akan bibit, pupuk, hingga pestisida. Harga sarana produksi itu ditentukan oleh pabrik dan pemerintah. Begitu pula dengan kontrol pemerintah atas harga beras sehingga petani tidak punya posisi tawar untuk menaikkan kesejahteraan mereka.
Sebagai petani, Suyoto pun belum maksimal menerapkan teknik pertanian organik. Karena doktrin pertanian konvensional yang berlangsung puluhan tahun, Suyoto masih malu dengan petani di kanan-kirinya untuk mengganti pupuk urea dengan pupuk kompos.
Apalagi percobaan penanaman padi dengan metode organik total hanya menghasilkan gabah tidak lebih dari 50 persen dibandingkan hasil dari pertanian hijau. Akhirnya, ia hanya memilih untuk tidak memakai pestisida sama sekali, tetapi masih mengandalkan pupuk urea. "Inilah akibat dari salah asuh yang sudah terlalu lama," kata Suyoto sambil tertawa.
TO Suprapto, Koordinator Nasional IPPHTI, juga mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menetapkan tahun 2010 sebagai tahun pertanian organik. Bila tahun 2010 disasar sebagai tahun pertanian organik, seluruh komponen yang mendukung pertanian organik perlu disiapkan.
Salah satu contoh kecil adalah minimnya data tentang pertanian organik di hampir semua institusi dinas pertanian di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Gerakan pertanian organik masih berupa aksi-aksi kecil di tingkat individu, dusun atau desa yang—biasanya—merupakan daerah dampingan suatu kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat.
"Karena itu, saya mengusulkan kampanye hasil pertanian organik sebagai produk sehat. Selain itu, pertanian organik harus meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi tidak memberatkan konsumen karena akan percuma saja bila produksi meningkat, namun daya beli masyarakat rendah," kata Suprapto.
Dalam perhitungan matematis produksi pertanian konvensional, petani bisa jadi hanya menjadi buruh sukarela untuk menanam dan merawat tanaman. Tenaga mereka sering kali tidak dimasukkan dalam komponen biaya produksi. Apalagi harga produk pertanian—terutama beras—bukanlah harga yang ditentukan petani sebagai produsen, melainkan harga yang sudah ditetapkan secara baku oleh pihak yang berkuasa (baca: pedagang dan pemerintah), melalui mekanisme pasar dengan berbagai dalih, seperti pengamanan stok pangan nasional.
Katamso, Ketua Kelompok Tani Organik Gemari di Dusun Jomboran, Desa Sendangagung, Minggir, Sleman, pernah menghitung besarnya pengeluaran untuk satu kali masa tanam. Harga satu kilogram bibit setara dengan sekilo beras, yakni antara Rp 3.500 hingga Rp 5.000 per kilogram. Untuk 1.000 meter persegi tanah dibutuhkan 5 kilogram bibit.
Sedangkan kebutuhan pupuk urea untuk tanah seluas 1.200 meter persegi mencapai 50 kilogram. Bila beruntung, petani bisa mendapatkan pupuk urea bersubsidi seharga Rp 52.500 untuk 50 kilogram. Selain urea, masih berjenis pupuk kimia lain yang harus dikonsumsi padi hibrid itu.
Pengeluaran petani masih ditambah dengan sejumlah komponen jasa, seperti ongkos traktor, membayar tenaga buruh tanam, dan biaya jasa lain. Belum lagi biaya untuk sewa tanah atau penyusutan lahan.
Untuk biaya produksi, petani harus merogoh hingga Rp 400.000. Hasil yang diperoleh sekitar 2,75 kuintal beras, untuk jenis panenan tergolong baik. Bila petani mengolah sendiri pascaproduksi seluruh, beras ini setara dengan Rp 962.500.
Namun, sejumlah pengeluaran pascapanen, seperti penjemuran serta penggilingan dari gabah menjadi beras, juga harus dilakukan sendiri. Belum lagi bila padi dikonsumsi sendiri, sekitar empat bulan masa tanam. "Mengerikan sekali kalau harus menghitung hasil pertanian kimia. Sepertinya, usaha petani tidak ada harganya," tutur Katamso.
Karena perhitungan yang begitu mencekik petani, Katamso memilih untuk menerima pelajaran bertani organik. Di bawah bimbingan petani dari Dusun Kleben, Godean, Sleman, Katamso dan belasan petani Jomboran belajar membuat pupuk kompos.
Keberpihakan
Di tengah mulai berakarnya pertanian organik yang telah dirintis selama 6 tahun, Suratman, petani di Dusun Temon, Desa Banyuaeng, Karangnongko, Klaten, justru memilih untuk meninggalkan metode pertanian organik dan kembali ke pertanian hijau.
Alasannya sederhana: rantai pemasaran yang selama ini dijalankan kelompok pertanian Sari Pratiwi mandek sejak tahun 2004. Akibatnya, ia lebih senang bertani secara praktis dengan memanfaatkan sarana produksi kimia.
"Hasil yang didapat dari pertanian organik juga tidak sebanyak pertanian dengan kimia. Karena itu, saya memilih memakai pupuk kimia dan pestisida saja."
Beras dari "pertanian hijau" (memakai urea) telah memberinya hasil lebih banyak. Sedangkan teknologi organik hingga kini belum bisa memberi hasil maksimal yang meyakinkan bahwa pertanian organik meningkatkan kesejahteraan.
Suratman dan petani lain banyak yang mengeluhkan problem pemasaran. Problem ini disebut-sebut juga oleh Direktur Komunitas Bunderan (UGM Yogyakarta) Gutomo Priyatmono sebagai salah satu masalah yang perlu dipecahkan untuk mendongkrak popularitas pertanian organik.
"Fokus kami pada perluasan pasar. Ketika pasar tidak ada, pertanian organik akan mati. Bila kita ingin menghargai produk pertanian organik, maka harga beli gabah petani tinggi. Akhirnya berujung pada mahalnya produk pertanian," ucap Gutomo.
Harga gabah organik yang tinggi memicu harga beras organik juga mahal. Buntutnya konsumen yang bisa membeli produk pertanian organik akan terbatas sehingga daya serap produk organik ini tidak bisa sebesar beras konvensional yang murah, apalagi beras raskin. Terpautnya harga setidaknya Rp 2.000 per kilogram.
Peneliti Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan (PSKP) UGM Mochammad Maksum menambahkan, akademisi di kampus merupakan pihak yang ikut melanggengkan pertanian kimia karena dari situ para akademisi memperoleh proyek.
"Coba Anda masuk perguruan tinggi. Faktanya, berjubel akademis nge-gong-i pendekatan kimiawi dan teramat langka yang melirik organik. Mengapa? Karena akademisi lebih suka proyek," ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Antonius Budisusila, mengatakan, trauma petani atas peristiwa tahun 1950-1960-an merupakan bagian dari politik ingatan yang membuat petani malas kembali memakai pertanian organik. Petani dihadapkan pada fakta orang antre bahan pangan dan penghapusan paksa memori bertani organik. Petani yang menolak sistem pertanian modern dengan bahan-bahan kimia akan dicap sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dari sisi struktural, petani menghadapi sejumlah masalah yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Petani penggarap tentu akan enggan beralih jadi petani organik.
Apalagi sewa tanah tidak dilakukan secara bagi hasil, melainkan dibayar tunai. Akibatnya, petani enggan mencoba metode pertanian yang dianggap "baru", seperti pertanian organik.
Di samping itu, petani menghadapi tawaran tiada henti untuk memperbesar keran konsumsi mereka dengan kemudahan mendapatkan kredit atau pinjaman (termasuk dari pemerintah).
Karena itu, sejumlah agenda reformasi agraria mendesak untuk segera dilaksanakan. Misalnya, membuka kesempatan petani mengakses tanah kas desa. Namun, kepentingan ini masih harus berhadapan dengan tuntutan meningkatkan pemasukan desa yang berbuntut pada keberpihakan desa kepada pemodal.
Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan. Apalagi dengan disertasi tentang masyarakat desa yang telah dilakukan pimpinan bangsa ini diharapkan kebijakan negara untuk ketahanan pangan bisa semakin dekat dengan petani sebagai produsen pangan (Agnes Rita Sulistyawaty)
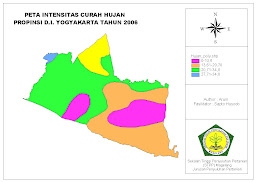
Tidak ada komentar:
Posting Komentar